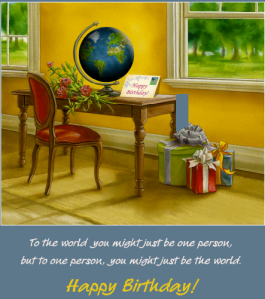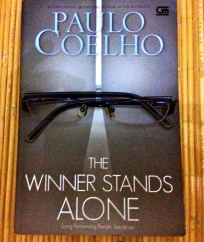Nanar kupandang sajian nasi campur vegetarian di hadapanku. Pikiranku tidak sedang menyatu dengan ragaku. Suara percakapan orang-orang di beberapa meja di rumah makan timbul tenggelam di kepala ku. Hujan membuat kami tak bisa duduk di kursi luar atau gazebo di taman terbuka restauran. Sebagai gantinya kini kami duduk di meja pojok, di bawah lukisan safana yang didominasi warna kuning di atasku. Waktu telah menunjukkan jam tujuh malam. Resah ku santap paduan sate, daging bakar, ikan bumbu bali, sayuran disiram sambal kacang dan setumpuk kecil emping goreng yang semua berbahan non-daging. Menu vegetarian yang disajikan dalam piring beralas daun pisang membuat seakan semua daging tiruan tersebut menonjol mendekati penampilan aslinya, kecuali rasanya yang tentu saja tak bisa diimitasi.
Hatiku riuh seperti sedang diterjang angin puting beliung. Hal itu membuatku harus mengerahkan segenap daya untuk mendengar, mencerna dan memberi tanggapan wajar di tiap tukar kata dalam pembicaraan kami. Ya, kami sedang bercakap tentang hujan yang seharian mengguyur kota, kabar selama kami lama tidak berjumpa, binatang, kesukaan, makanan, juga lainnya entah apa. Musik menjadi hal pertama sejak kami duduk di meja, saat makanan yang kami pesan belum disajikan hingga gelas minuman kedua dia tandaskan. Semua nama dan musik yang aku suka tiba-tiba tak mampu aku eja. Ingatanku menjadi tak setia karena di dalam diriku sedang berusaha menahan agar pikiran dan hatiku tak pecah berantakan.
Berbincang dengan mu adalah menghidupi paradoks keterasingan dan menemukan penggalan siapa diriku. Saat ini aku hampir merasakan benci mengingat kenyataan yang melingkupi mu dan diriku, kenyataan yang menghidupi kita. Kenyataan yang tak senyaman membayangkan embun pagi yang menjadi bagian romantisme terbitnya mentari atau banyangan camar terbang indah di saat mentari tenggalam ditepi lautan. Hatiku terasing dari mimpi yang tak disetujui oleh logikaku. Tapi ada saatnya kita terhubung begitu saja oleh banyak kesamaan yang barangkali tak pernah kita sangka. Kita menyukai membangun dunia lewat fantasi dan untain kata-kata. Menggapai kedamaian dengan menyusuri mutiara kata para pejungga dan pengembara kehidupan adalah hal yang kita suka. Terasa alami dua hal itu menarik kita dalam pusaran luapan kegembiraan begitu saja. Melihat pendar semangat dimatanya saat merangkai harapan dan rencana perjalanan yang dia sedang susun dalam hidupnya membuat semua hal disekitar kami menjadi hilang. Pelayan yang hilir mudik membawa mengantar pesanan dan melayani permintaan tiap meja, temaram lampu restauran, perabot kayu dan dekorasi ruangan menjadi kosong tertelan oleh lautan di matanya.
Gagang cangkir didepanku terasa begitu jauhnya untuk kujangkau. Saat aku berhasil meraihnya sendok gula kecil disebelahnya berdentang jatuh membuat dadaku berdetak makin kencang. Aku seperti terseret dalam pusaran yang makin membesar karena aku gagal untuk menghentikan diriku agar tidak melawan. Melepaskan pertarungan batin agar bisa menghidupi ‘kekinian’, momen dimana aku sedang bernafas, tak juga sanggup aku lakukan. Suara yang keluar dari mulutku; canda, argumen, cerita dan jawaban tanya hanya sayup terdengar ditelingaku sendiri. Gerangan keterbelahan rasa dan pikiran yang membuat aliran kata-kata kita tercekat di banyak tikungan pertimbangan. Hingga, dialog yang ada adalah kekakuan dan kekawatiran untuk melakukan kesalahan.
Saat gelisah tak terbendung, kita akhiri pertemuan dengan tatap yang tak saling tahu arti dan jawabnya. Selain, kepasrahan bahwa kita gagal mengikatkan hati dan pikiran untuk janji dilain pertemuan. Sepanjang jalan perpisahan seakan memantapkan ketakbersuaan abadi yang menundukkan kita dalam pedihnya kegelisahan.
Kembali mataku nanar. Saat kutemukan pesan surat elektronik yang kau kirimkan menghayutkan resah dalam sekejap: “Hi!”
ada benang penghubung diantara kita
tarik menarik mentautkan jiwa
terhubung dalam keterpisahan waktu, ruang dan jarak
resah saat kau hilang dari aku mengarah
parau suaraku saat nyanyimu hilang dari hatiku
relung jiwaku hampa saat genta kehidupan mengaburkan dawai musikmu
pekat pandangku kala dirimu berpaling dari melihatku
hi
hatiku tak berikrar
cinta belum berwajah
rindu meragu untuk diberi nama dengan namamu
kapan benang pengikat hati ini terulur?
tak tahu siapa yang memintalnya
helai-helainya menjerat dan membuat kita
satu nafas saat saling mengingat
bahagia hanya oleh esensi saling merasa yang tak selalu perlu diartikan
hadirnya hanya untuk kita nikmati bersama
warna-warni helai itu seperti pelangi
seliris namamu saat hatiku tergetar mengingatmu
semanis saat kau mimikirkan diriku dalam keyakinanku
hi …
saat ini sehelai benang biru yang kutitipkan untukmu
untaiannya sedang menyapamu
mempertemukan jiwaku dan jiwamu
menjeratku kian erat saat aku memanggilmu…. hi.
(Jakarta, 22 Januari 2015)


 Mengenang kelahiranmu adalah meniti kembali ingatan romantis sebagai seorang ibu. Saat itu purnama terang menyinari langit kota tenang di kaki gunung Slamet. Dini hari jam tiga pagi membelah dingin kota berkendara motor mengantarkan kelahiranmu. Sendirian, kita tinggalkan saudara perempuanmu yang sedang demam di tempat tante di kosan. Kau hadir dalam hitungan jam dengan kelegaan yang nyaris kupertanyakan kenapa sakit saat kelahiranmu hanya tipis dan sebentar saja.
Mengenang kelahiranmu adalah meniti kembali ingatan romantis sebagai seorang ibu. Saat itu purnama terang menyinari langit kota tenang di kaki gunung Slamet. Dini hari jam tiga pagi membelah dingin kota berkendara motor mengantarkan kelahiranmu. Sendirian, kita tinggalkan saudara perempuanmu yang sedang demam di tempat tante di kosan. Kau hadir dalam hitungan jam dengan kelegaan yang nyaris kupertanyakan kenapa sakit saat kelahiranmu hanya tipis dan sebentar saja.